Cocke
Lane, jalanan yang kuinjak ini memilki nuansa yang kental akan kepekatan warna
hitam berdosa. Atau mungkin hanya aku yang menganggapnya begitu?
Setiap
langkahku di kelilingi bangunan kokoh angkuh yang menyombong ria. Mereka
menutup pintunya rapat ketika tak sengaja ku lihat mereka tertawa dalam balutan
mantel-mantel berbulu mahal yang pastinya terasa hangat. Seolah membiarkanku
melihat kehangatan mereka barang semenit saja akan membawa pada sebuah musibah.
Ya,
beruntungnya mereka. Berselanjar kaki menikmati acara televisi dengan
mantel-mantel tebal yang melekat. Jangan lupakan bangunan tempat mereka
bersembunyi, kokoh dan kuat, tak membiarkan udara dingin yang menggigit ini
mencari celah barang sekecil pun.
Bagaimanapun,
aku selalu iri dengan rumah orang. Hangat dan nyaman. Rumah yang menjalankan
fungsinya dengan benar. Bukan rumah berpenghuni yang kehilangan kehangatan dan
rasa aman yang harusnya menjadi bagian darinya. Rumahku jauh disana, rumahku
telah pergi.
Malam, dingin dan gelap, ku rekatkan kembali jaket yang menempel ditubuh, berusaha menempelkan kain yang sudah tipis itu dengan tubuh yang tersisa tulang ini. Mengedipkan mata, aku berusaha melihat jalanan yang masih terhampar di depan sana.
Kondisi
jalanan yang sempat diterpa air hujan membuat sepatu juga kaos kakiku basah,
menyalurkan hawa dingin yang membekukan pada kulit kakiku. Kepalaku tak
henti-hentinya terasa berputar membuat perjalanan terasa lebih panjang. Dengan
langkah sempoyongan, aku hanya mengandalkan pantulan sinar lampu jalan.
Setiap
langkah terasa semakin berat dan menyiksa tubuh. Sesuatu membisikan keraguan,
apakah semua yang telah ku lewati ini sepadan? Tetesan air melewatii pipiku,
tak perlu repot-repot menyekanya, pipiku malam ini memang sudah ku rencanakan
akan menjadi sungai deras akibat telah lama dibendung.
Tak
kuat mempertahankan keseimbangan, tembok dengan batu bata merah menjadi
sandaran punggungku. Namun ternyata ia tak cukup membantu, kepala yang terasa
berputar-putar serta badanku yang telah kehilangan energi akibat berjalan
sepanjang hari mempertemukan wajahku dengan aspal jalanan, material kasar yang
menghantarkanku pada ketidaksadaran yang merayap secara perlahan.
Lama
terdiam dalam keheningan, sesuatu terasa mulai aneh. Jalanan entah berantah
yang telah ku telusuri lambat laun membentuk siluet jalanan familiar yang ku
rindukan.
Rumah-rumah
pinggir jalan yang menjadi saksi masa kecilku kini berada persis di
kanan-kiriku. “apakah ini semacam patamorgana?”. suara tawaku
yang melengking tak mampu membangunkan para penghuni rumah di sepanjang jalanan
ini, buktinya tiada seorangpun datang memandangiku dengan penuh penilain,
meludahi ekesistensi keberadaanku kemudian mengecak pinggang dan
bersongot-songot mengatakan "dasar manusia buangan".
Angin
dingin membelai badanku dengan kejamnya. Kembali memeluk erat diri sendiri, kupejamkan
mata, berusaha berpikir bahwa semua ini tidak nyata. Aku tidak sekarat
menyedihkan saat ini. Aku berada di rumahku, menikmati kopi hangat dengan
kertas-kertas yang berserakan di mejaku.
Tiba-tiba sebuah sinar terang menarik perhatiaku. Pandanganku tertuju pada bangunan kelabu yang berada di barisan paling ujung dari kompleks perumahan yang tengah ku pijaki saat ini. Dari jauh dapat kulihat lampu-lampu di setiap ruangan samar-samar masih bersinar memancarkan cahaya kuning lembut yang membuatku mengingat kembali kenyamanan yang masih hidup disana.
Bagaikan
sebuah mantra, Kaki yang sedari tadi terasa tak bertenaga ini melangkah lebar
dengan cepat. Melewati setiap rumah yang berjejer di kanan dan kiriku.
“Bu?!”
Suara
besi berkarat termakan usia terdengar saat ku buka pagar rumah.
“Bu?!”
Mencari
sosok ibu, aku dengan pasti berlari menuju halaman belakang dan kutemukan
rumput panjang tak terurus telah memenuhi pekarangan. Satu pohon kokoh besar
berdiri tegak menggandeng ayunan kecil yang bergerak-gerak kecil tertiup angin.
Perasaanku
membuncah, tanpa bisa diungkapkan. Aku hanya berlari cepat menuju arahnya. Ku
peluk pohon tinggi kokoh itu, merasakan kehangatan pelukannya yang telah lama
tak kudapatkan.
Dulu
sekali, tempat ini merupakan tempat favoritku juga favorit ibu untuk bermain.
Ibu membawa pakaian yang akan di keringkan, sedang aku bermain, membawa bola
atau sekedar kotor-kotoran.
Ibu
merupakan seorang penyayang, ia senang membelai dan memelukku. Membuatkanku
makanan enak, menceritakanku sebuah dongeng setiap malam. Ia adalah rumahku.
Namun,
ketika ayah pergi menuju “rumahnya yang baru”, ibu berubah, ia sering terdiam
atau melamun tanpa alasan, tempat penuh kebahagiaan ini secara perlahan menjadi
tempat ibu menangis dan tertawa sendirian.
Ibu
berubah, ia semakin jarang memberikan belaian di kepalaku, atau usapan tangan
hangatnya di punggungku. Ia tidak tersenyum ataupun marah, ia hanya terdiam.
Suatu
hari ia memelukku dengan erat, aku tersenyum bahagia, "akhirya
ibuku kembali" ketika bibirnya mencium keningku aku memeluk
pinggangnya dengan erat yang dibalasnya dengan senyuman. Ia kembali memelukku
sebelum kemudian berbisik merdu di telinga kiriku.
“ibu
pergi dulu”. Aku mengangguk setuju, beberapa menit kemudian yang kulihat
hanya tubuh yang terbujur kaku. Tidak seperti ibu yang selalu menjawab semua
pertanyaannku, kini ia hanya terdiam, menggelantung, tapi mungkin ia masih
mendengar tangisanku.
Sudut
bibirku tertarik membentuk sebuah senyuman bahagia, namun air mata tak hentinya
menetes melewati pipiku.
“aku
juga pulang bu” dengan karmantel di leherku, aku meloncat. Membiarkan jalur
penapasan terhenti dan rasa sakit memakan tubuhku secara perlahan.




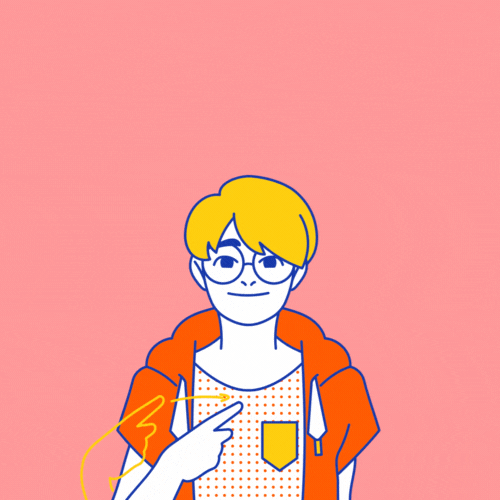




4 Komentar
Endingnya dark banget ini, :" aku enggak nyangka bakal segitunya. Kupikir si aku akan membawa ibunya ke rumah sakit.
BalasHapus😁Sebenarnya di dunia nyata dia blm meninggal, melainkan masih sekarat terkapar di aspal perumahan orang.
HapusEfek dari obat2an dan minuman yg dikonsumsi bikin kepalanya pusing dan berhalusinasi seolah2 dia kembali ke rumah dan bertemu ibunya yg sidah lama meninggal
Ending-nya kenapa? Kenapa se plot twist itu kak Hilla?
BalasHapusHehe, iya nih kak. Pengen coba bikin cerpen yg ada dark nya 😅
Hapus